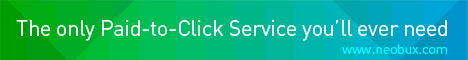MASYARAKAT INDONESIA MEMBANGUN
(MIM)
Tirta Sangga Jaya, dilihat dari perspektif sejarah, ternyata bukan sebuah berita besar. Nenek moyang bangsa Indonesia justru telah mengerjakan proyek-proyek yang Iebih besar dengan dukungan peralatan yang sangat sederhana. Apakah bisa diwujudkan? Ini mungkin pertanyaan yang dilontarkan setiap orang begitu melihat desain Tirta Sangga Jaya (TSJ) yang memang cukup mahal. Pertanyaan seperti ini tentunya sangat wajar mengingat besarnya dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan gagasan Tirta Sangga Jaya.
Bahkan, jika dilihat dari besarnya sumber daya yang digunakan, bisa dikategorikan sebagai proyek mercu suar. Akan tetapi, dari sisi manfaatnya, TSJ tidak pantas dikategorikan mercu suar dengan citra proyek gagah-gagahan, karena manfaatnya jauh lebih besar dari sumber daya yang digunakan untuk mewujudkan TSJ. Karma itu, Drs. Mushoddiq (46), Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) Cipta Karya Informatika (CKI) Jakarta dan Dosen Sekolah Tinggi ilmu Ekonomi (STIE) IPWIJA, mengatakan tantangan apa pun yang dihadapi, tidak seharusnya menjadi penghambat untuk mewujudkan TSJ.
“Soalnya, perwujudan TSJ ditunggu banyak orang dan dibutuhkan seluruh warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi,” katanya ketika ditemui Berita Indonesia di sela-sela aktivitas mengajarnya, Jumat (18/5).
Mushoddiq yang juga pengajar bidang studi sejarah di SMU Negeri 103 ini, mengatakan proyek pengendalian banjir TSJ sebenarnya bukan sesuatu yang terlalu besar dari perspektif sejarah. “Nenek moyang kita sudah mengerjakan hal-hal yang setara dengan TSJ di awal tarik Masehi,” katanya.
Ia merujuk Raja Purnawarman yang memimpin Kerajaan Tarumanegara (400-500M), membangun proyek saluran air pengendalian banjir dan irigasi, bernama Sungai Candrabhaga, sepanjang 6.122 busur atau 11 kilometer. Yang sangat memukau dari pembuatan Sungai Candrabhaga (Bekasi) dan Gomanti (Kali Mati, Tangerang). Penggalian sungai itu diselesaikan hanya dalam waktu 21 hari melibatkan puluhan ribu orang. Raja Purnawarman memotong 1.000 ekor sapi untuk selamatan selesainya pembuatan sungai tersebut.
Menurut prasasti Tugu, Cilincing, Jakarta Utara, peninggalan abad kelima dari raja yang beragama Hindu ini sudah memperhatikan pengendalian banjir di musim hujan dan melindungi petani dari kekeringan pada musim kemarau. Sejarahwan Belanda, DR J Ph Vogel yang pernah menstrakripsi dan menelaah Prasasti Tugu, kini berada di Museum Nasional, sang raja sangat memperhatikan pengairan sawah-sawah para petani. Artinya, kerajaan ini sudah mencapai taraf yang tinggi di bidang pertanian.
Berdasarkan Prasasti Tugu dan prasasti-prasasti lainnya, kekuasaan Kerajaan Tarumanegara meliputi wilayah Banten, DKI Jakarta, Bogor, Bekasi dan Citarum. Kata Chandra dalam Chandrabhaga, berarti sari atau bulan. Chandrabhaga artinya sama dengan Kali Bagasasi, kemudian berubah jadi Bhagasi atau Bekasi sekarang.
Prasasti Tugu dan Chandrabhaga terletak di antara lokasi yang sama jauhnya. Ini mencerminkan pelestarian keseimbangan ekosistem. Sang raja menempuh kebijakan pemukiman yang juga didasarkan pada azas keseimbangan ekologis. Karenanya, raja memperbolehkan rawa-rawa di pedalaman diuruk untuk pemukiman. Maka muncul nama-nama, seperti Rawa Bangke, Rawa Puter atau Rawa Puter. Tetapi rawa-rawa di pesisir pantai tidak boleh diurug untuk pemukiman, karena merupakan kawasan hutan (bakau) lindung dan resapan air.
Atas kerja kerasnya, para sejarahwan memberi apresiasi yang sangat luar biasa terhadap karya monumental Raja Purnawarman tersebut. Sampai saat ini, karya besar Raja Purnawarman masih dapat dinikmati oleh masyarakat Jakarta. Menurut para arkeolog, Sungai Bagasasi di abad ke-5, sudah berganti nama menjadi Kali Bekasi.
Sumber : Tirtasanggajaya.blogspot