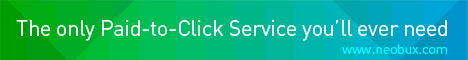MIM
Seorang ulama Nurcholish Madjid mencatat ada indikasi sejak zaman Nabi Sulaiman bahwa Arab mengimpor kapur untuk dibuat minuman tonic dari Barus (orang-orang Melayu di wilayah sumatera) sehingga menjadi perumpamaan kehidupan surgawi yang di abadikan dalam Al-Qur’an (wayusqauna biha ka’san kana mizajuha kafura).
Ada sebuah ayat dalam Al-Qur’an yang cukup menarik perhatian saya. Dalam surah al-A’raaf ayat 96 difirmankan, “Walau anna ahlal-quraa aamanuu wattaqau lafatahnaa `alaihim barakaatim minas-samaa’ i wal-ardhi” (jika para penduduk desa beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi). Hemat saya, sepertinya ayat ini tidak ditujukan kepada orang-orang Arab waktu itu yang menjadi pendengar Nabi Saw. Benar, memang Al-Qur’an itu bagi seluruh umat manusia, tetapi ayat ini secara khusus sedang membicarakan suatu kaum tertentu. Suatu bangsa yang telah mengenal peradaban yang tinggi, yang telah berbudaya, yang mengenal suatu sistem pemerintahan yang telah tertata.
Yang mendapatkan penekanan di ayat tersebut —menurut K.H. Maemun Zubair, salah seorang sesepuh Nahdlatul Ulama— adalah ahlal-quraa, yang artinya para penduduk desa. Ini menarik sekali, menurut saya penduduk “desa” atau “nagari” ini banyak sekali di Indonesia. Saat ini desa di Indonesia saja sudah mencapai ribuan jumlahnya. Bagaimana dengan di Jazirah Arab saat itu? Menurut Kiai Sepuh itu dalam ceramahnya pada puncak Haul Pesantren Buntet Cirebon 11/03/2006, “Di Arab tidak ada desa. Adanya (waktu turun ayat itu) adalah suku Badui yang hidupnya (nomaden) seperti tawon, kalau kepala sukunya pindah mereka ikut pindah. Makanya, ayat ini untuk Indonesia”.
Jadi jelas pengertian desa yang menetapkan diri selamanya di suatu wilayah hukum, tidak sama dengan nomaden. Sebuah desa, dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah tatanan kemasyarakatan yang diberi kewenangan mengatur dirinya sendiri sesuai budaya setempat, berbeda dengan kelurahan. Sebuah kelurahan tidak mengatur dirinya sendiri. Ia setidaknya tidak mengikatkan hukum pada tradisi dan adat istiadat yang kental seperti pada sebuah desa. Di Cirebon misalnya, kepala desa lazim disebut Kuwu. Ia bukan seorang pegawai negeri, tapi yang dituakan, yang dihormati dan dinobatkan oleh warganya. Berbeda dengan kelurahan, seorang Lurah diangkat oleh pemerintahan yang lebih tinggi, ia seorang pegawai negeri.
Nomaden itu pola hidup berpindah-pindah, tidak menetap di suatu tempat. Jadi budaya yang mapan tidak tercipta dalam hidup nomaden seperti ini. Hukum yang berlaku masih sangat sederhana, seringkali kepala suku memerintah secara sewenang-wenang dan despotik a La Genghis Khan. Nomaden itu boleh dibilang pola hidup yang masih primitif bila dinilai orang modern saat ini.
Nampak dalam ayat itu, Nabi Muhammad memiliki visi yang jauh sekali. Seolah-olah Nabi ingin menyampaikan pesan kepada pengikutnya yang masih nomaden itu suatu ketika mereka mampu memiliki sistem pemerintahan yang tertata, yang beradab dan berbudaya.. yaitu masyarakat desa, masyarakat berbudaya yang beriman dan bertakwa, seperti disebut dalam ayat itu. Dan, kriteria desa seperti itu adanya di bumi Nusantara yang masuk peradaban besar Shind/Indies. Kenapa? Karena Nabi sendiri bersabda,”belajarlah sampai ke negeri Shind”.
Amat logis, Nabi akan menganjurkan orang belajar ke negeri-negeri yang maju, yang pantas dijadikan teladan. Mungkin dalam pandangan Nabi, negeri Shind adalah negeri yang mendapat berkah dari langit dan bumi, sehinga pantas dicontohi oleh para pengikutnya.
*Di kala Barat masih hidup di gua-gua, di kala Arab masih mukim di tenda-tenda, bangsa kita sudah mengekspor rempah-rempahnya dengan maskapai sendiri ke Afrika dan tempat2 lainnya di belahan dunia.*
Ada juga hadis dari Ibu Aisyah ra bahwa saat haji perpisahan, tahallul dan ihram, tubuh Nabi diolesi Dzarirah (bedak wangi dari Shind/Indies) . Di sini tidak semata-mata Nabi menggunakan term ahlal-quraa, jika ia belum pernah melihat rupa desa atau nagari atau negeri sebelumnya. Mungkin saat berdagang semasa muda, Nabi pernah singgah di desa-desa di wilayah peradaban Shind.
Nabi ingin mewujudkan masyarakat madani, atau dengan kata lain, penguatan masyarakat sipil (civil society) seperti yang pernah ia saksikan di Shind selama perjalanan berdagang. Jangan lagi terjebak dalam konsep iman dan takwa yang formalistik ritual model agama tertentu, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kesalehan sosial, dalam kasih terhadap umat manusia yang satu adanya sehingga tertata kehidupan yang damai, aman, tentram dan sejahtera (maslahah ‘ammah atau bonum commune).
Saya meyakini ayat dalam surah al-A’raaf ini relevan dengan bangsa Indonesia sejak turunnya yang kali pertama hingga kini. Utamanya bagi orang-orang awam di grass root yang hidup di desa-desa. Sekarang yang penting adalah desanya. Kunci keberkahan adalah desa, dan desa tidak lepas dari kehidupan budaya. Desa, menurut saya adalah cagar budaya. Hatta setiap desa punya adat istiadat dan tradisi yang khas, namun mirip-mirip karena masih dalam lautan budaya Nusantara. Budaya bangsa kita adalah suka hidup dalam damai. Apresiatif terhadap perbedaan. Kekerasan bukanlah budaya kita.
Sekarang terlihat jelas ada upaya kelompok agama yang mencuci otak warga bangsa ini hingga ke pelosok desa supaya ingkar budaya sendiri. Itu bertentangan dengan visi Nabi di atas.
*Mengingkari budaya, menolak kebhinekaan berarti mendustakan ayat-ayat Tuhan* adalah suatu perbuatan yang niscaya mengundang azab seperti disebutkan dalam surah Al-A’raaf berikutnya, “wa laakin kadzdzabuu fa akhadznaahum bimaa kaanuu yaksibuun”.
Nabi tidak menolak tradisi di Arab seperti tradisi thawaf, haji, puasa, dan lain-lain yang lazim diselenggarakan orang-orang Arab jauh sebelum kenabiannya. Nabi mengapresiasinya sebagaimana difirmankan, “wa kadzalika anzalnahu hukman `rabiyan (demikianlah Aku turunkan Al-Qur’an itu kepadanya berupa hukum-hukum yang telah berlaku dalam masyarakat Arab).
Sejarah mencatat, bangsa kita menerima masuknya agama-agama manapun tanpa melalui perang dan paksaan. Begitu pun Islam, orang-orang Indonesia menerima agama ini dengan damai. Mereka ini yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bahkan kini Islam menjadi agama mayoritas. Islam menyebar secara gegantis lewat pesantren-pesantren kita yang menjadi ciri khas Islam di Indonesia. Bandingkan dengan Dinasti Moghul di India. Sudah beratus tahun dinasti ini berkuasa, toh tetap gagal menjadikan Islam sebagai mayoritas di sana.
Orang-orang Indonesia masuk Islam pada masa akhir-akhir. Islam menyebar ke Maroko, Tunisia dan Asia pada abad ke-7. Islam masuk pertama kali ke Aceh pada abad ini, tetapi tidak berkembang. Justru Islam berkembangnya di Jawa pada akhir abad ke-15 atau ke-16 hingga menyebar ke seluruh Nusantara. Ini dilakukan dengan cara-cara pendidikan pesantren. Untuk pertama kalinya adalah pesantren Ampel Dento, yang serambi masjidnya bukan model Arab, melainkan mengadopsi Pendopo Brawijaya.
Apa yang diteladankan Sunan Ampel dengan pesantrennya itu, adalah Islam yang mengapresiasi budaya kita sendiri, tanpa harus meniru-niru Arab. Sehingga Islam bisa tersebar dengan damai, tanpa menyakiti awam di desa-desa karena tercerabut dari akar budayanya. Masjid yang dibangun Sunan Kudus juga mirip bangunan Pura, tempat suci agama Hindu.
Di Cirebon, masih ditemukan kantor-kantor instansi pemerintah dan masjid yang dibangun gapura di halamannya mengadopsi arsitektur candi. Islam di Jawa tidak disebarkan dengan sebentuk representasi Islam radikal a la Wahhabi seperti yang dilakukan kaum Padri di Sumatra yang mengakibatkan pertumpahan darah. Tradisi pesantren di Jawa mengajarkan cara-cara damai dalam beragama selaras dengan budaya Nusantara, tidak dengan kekerasan.
Iman dan takwa dalam al-A’raaf ayat 96 itu tidak dimaknai secara eksklusif milik orang beragama resmi Islam saja tapi inklusif. Islam yang dipakai adalah maknanya yang generik, yaitu kedamaian, kepasrahan total kepada Tuhan dan seterusnya. Apapun agama dan kepercayaannya, asalkan ia beriman dan bertakwa, artinya melakoni agama atau kepercayaannya dalam hidup sehari-hari itulah yang bisa mendatangkan berkah. Saling memperkuat dengan ayat al-A’raaf di atas, maka dalam surah al-Maidah (5:66) difirmankan: “Dan sekiranya mereka mengikuti ajaran Taurat dan Injil serta segala yang diturunkan dari Tuhan kepada mereka, niscaya mereka akan menikmati kesenangan dari setiap penjuru.”
Di ayat lain Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 62, “Orang-orang beriman (orang-orang Muslim), Yahudi, Kristen, dan Shabi’in yang percaya kepada Allah dan hari kiamat, serta melakukan amal kebajikan akan beroleh ganjaran dari Tuhan mereka. Tidak ada yang harus mereka khawatirkan, dan mereka tidak akan berduka”. (Catatan saya: terjemahan Shabi’in versi Depag adalah orang-orang yang mengikuti syariat nabi-nabi zaman dahulu atau yang menyembah bintang atau dewa-dewa). Pengertian iman dan takwa semacam ini (yaitu percaya kepada Allah, hari kiamat dan beramal kebajikan tak penting agama formalnya apa) kiranya yang dimaksudkan dalam surah al-A’raaf ayat 96 tersebut yang bisa menghadirkan keberkahan di muka bumi.
Itulah keunikan dan kearifan bangsa Indonesia yang telah terkenal sejak dulu kendati bersentuhan dengan beragam agama, namun tetap mengapresiasi dan tidak mengingkari budayanya sendiri. Kekerasan agama yang terjadi di Sumatra karena kaum Padri menolak budaya, mereka merujuk kekerasan budaya Arab.
Wali Songo yang di kemudian hari terperangkap politik kekuasaan akhirnya kembali —meminjam ejekan penulis Wedhatama di abad ke-19— “anggubel sarengat” model Arab hingga berujung pada tragedi berdarah di Jawa. Wali Songo yang dibutakan oleh kekuasaan akhirnya lupa bahwa saat Islam baru lahir, budaya kita telah mapan, telah punya desa-desa sebagai cagar budaya yang banyak jumlahnya. Mereka lupa bahwa paradigma luar tak bisa dipaksakan terhadap agama.
Tidak hanya Islam, agama manapun berkembang di negara-negara yang berbeda dengan cara-cara yang berbeda pula. Leif Manger misalnya melihat agama bukan persoalan hitam putih, bukan persoalan tunggal, milik Timur Tengah, tetapi Islam dimungkinkan melakukan dialektika yang dinamis. Antara Islam dalam kategori universal dengan lokalitas dimana ia hidup. Hal ini dikarenakan sekalipun Islam memiliki karakter universal, ia juga merupakan produk dari pergulatan dengan konteks lokal, dengan budaya setempat.
Dalam landasan budaya Nusantara inilah bangsa Indonesia yang majemuk bisa duduk bersama, itulah implementasi iman dan takwa. Jika bangsa ini bisa duduk bersama tanpa membedakan latar belakang dalam landasan budaya, maka hujan berkah tanpa diharapkan pun akan datang dengan sendirinya seperti disitir dalam surah al-A’raaf tersebut. Luar biasa, di masa lalu sepertinya Baginda Nabi telah “menyaksikan” Nusantara yang penuh berkah. Berabad-abad yang lalu, Nabi pun telah “melihat” kebangkitan Indonesia di masa depan.
Kebangkitan yang dimaksud adalah kebangkitan wajah agama yang moderat (wasatha). Kebangkitan itu adalah kebangkitan budhi (kesadaran), seperti dibilang Guru Besar dari Sumatra, Dharmakirti seribu tahun lalu. Kebangkitan itu adalah kebangkitan esensi agama-agama yang berwajah ramah, yang hormat pada Ibu Pertiwi.
Pemahaman “Islam”, “iman dan takwa” yang demikian luar biasa ini, kendati bangsa Indonesia memeluk “Islam” pada masa-masa akhir zaman persebaran Islam, karuan saja membuat Nabi Saw berdecak kagum, “A’jabu iimanan ummatin awakhiri ummati laa yudrikuunii walaa yaraaka ashaabii” (sungguh mengagumkan keimanan umat akhir zaman, yang tidak ada di zamanku dan para sahabatku
sumber : .alfisatria.
Ada sebuah ayat dalam Al-Qur’an yang cukup menarik perhatian saya. Dalam surah al-A’raaf ayat 96 difirmankan, “Walau anna ahlal-quraa aamanuu wattaqau lafatahnaa `alaihim barakaatim minas-samaa’ i wal-ardhi” (jika para penduduk desa beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi). Hemat saya, sepertinya ayat ini tidak ditujukan kepada orang-orang Arab waktu itu yang menjadi pendengar Nabi Saw. Benar, memang Al-Qur’an itu bagi seluruh umat manusia, tetapi ayat ini secara khusus sedang membicarakan suatu kaum tertentu. Suatu bangsa yang telah mengenal peradaban yang tinggi, yang telah berbudaya, yang mengenal suatu sistem pemerintahan yang telah tertata.
Yang mendapatkan penekanan di ayat tersebut —menurut K.H. Maemun Zubair, salah seorang sesepuh Nahdlatul Ulama— adalah ahlal-quraa, yang artinya para penduduk desa. Ini menarik sekali, menurut saya penduduk “desa” atau “nagari” ini banyak sekali di Indonesia. Saat ini desa di Indonesia saja sudah mencapai ribuan jumlahnya. Bagaimana dengan di Jazirah Arab saat itu? Menurut Kiai Sepuh itu dalam ceramahnya pada puncak Haul Pesantren Buntet Cirebon 11/03/2006, “Di Arab tidak ada desa. Adanya (waktu turun ayat itu) adalah suku Badui yang hidupnya (nomaden) seperti tawon, kalau kepala sukunya pindah mereka ikut pindah. Makanya, ayat ini untuk Indonesia”.
Jadi jelas pengertian desa yang menetapkan diri selamanya di suatu wilayah hukum, tidak sama dengan nomaden. Sebuah desa, dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah tatanan kemasyarakatan yang diberi kewenangan mengatur dirinya sendiri sesuai budaya setempat, berbeda dengan kelurahan. Sebuah kelurahan tidak mengatur dirinya sendiri. Ia setidaknya tidak mengikatkan hukum pada tradisi dan adat istiadat yang kental seperti pada sebuah desa. Di Cirebon misalnya, kepala desa lazim disebut Kuwu. Ia bukan seorang pegawai negeri, tapi yang dituakan, yang dihormati dan dinobatkan oleh warganya. Berbeda dengan kelurahan, seorang Lurah diangkat oleh pemerintahan yang lebih tinggi, ia seorang pegawai negeri.
Nomaden itu pola hidup berpindah-pindah, tidak menetap di suatu tempat. Jadi budaya yang mapan tidak tercipta dalam hidup nomaden seperti ini. Hukum yang berlaku masih sangat sederhana, seringkali kepala suku memerintah secara sewenang-wenang dan despotik a La Genghis Khan. Nomaden itu boleh dibilang pola hidup yang masih primitif bila dinilai orang modern saat ini.
Nampak dalam ayat itu, Nabi Muhammad memiliki visi yang jauh sekali. Seolah-olah Nabi ingin menyampaikan pesan kepada pengikutnya yang masih nomaden itu suatu ketika mereka mampu memiliki sistem pemerintahan yang tertata, yang beradab dan berbudaya.. yaitu masyarakat desa, masyarakat berbudaya yang beriman dan bertakwa, seperti disebut dalam ayat itu. Dan, kriteria desa seperti itu adanya di bumi Nusantara yang masuk peradaban besar Shind/Indies. Kenapa? Karena Nabi sendiri bersabda,”belajarlah sampai ke negeri Shind”.
Amat logis, Nabi akan menganjurkan orang belajar ke negeri-negeri yang maju, yang pantas dijadikan teladan. Mungkin dalam pandangan Nabi, negeri Shind adalah negeri yang mendapat berkah dari langit dan bumi, sehinga pantas dicontohi oleh para pengikutnya.
*Di kala Barat masih hidup di gua-gua, di kala Arab masih mukim di tenda-tenda, bangsa kita sudah mengekspor rempah-rempahnya dengan maskapai sendiri ke Afrika dan tempat2 lainnya di belahan dunia.*
Ada juga hadis dari Ibu Aisyah ra bahwa saat haji perpisahan, tahallul dan ihram, tubuh Nabi diolesi Dzarirah (bedak wangi dari Shind/Indies) . Di sini tidak semata-mata Nabi menggunakan term ahlal-quraa, jika ia belum pernah melihat rupa desa atau nagari atau negeri sebelumnya. Mungkin saat berdagang semasa muda, Nabi pernah singgah di desa-desa di wilayah peradaban Shind.
Nabi ingin mewujudkan masyarakat madani, atau dengan kata lain, penguatan masyarakat sipil (civil society) seperti yang pernah ia saksikan di Shind selama perjalanan berdagang. Jangan lagi terjebak dalam konsep iman dan takwa yang formalistik ritual model agama tertentu, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kesalehan sosial, dalam kasih terhadap umat manusia yang satu adanya sehingga tertata kehidupan yang damai, aman, tentram dan sejahtera (maslahah ‘ammah atau bonum commune).
Saya meyakini ayat dalam surah al-A’raaf ini relevan dengan bangsa Indonesia sejak turunnya yang kali pertama hingga kini. Utamanya bagi orang-orang awam di grass root yang hidup di desa-desa. Sekarang yang penting adalah desanya. Kunci keberkahan adalah desa, dan desa tidak lepas dari kehidupan budaya. Desa, menurut saya adalah cagar budaya. Hatta setiap desa punya adat istiadat dan tradisi yang khas, namun mirip-mirip karena masih dalam lautan budaya Nusantara. Budaya bangsa kita adalah suka hidup dalam damai. Apresiatif terhadap perbedaan. Kekerasan bukanlah budaya kita.
Sekarang terlihat jelas ada upaya kelompok agama yang mencuci otak warga bangsa ini hingga ke pelosok desa supaya ingkar budaya sendiri. Itu bertentangan dengan visi Nabi di atas.
*Mengingkari budaya, menolak kebhinekaan berarti mendustakan ayat-ayat Tuhan* adalah suatu perbuatan yang niscaya mengundang azab seperti disebutkan dalam surah Al-A’raaf berikutnya, “wa laakin kadzdzabuu fa akhadznaahum bimaa kaanuu yaksibuun”.
Nabi tidak menolak tradisi di Arab seperti tradisi thawaf, haji, puasa, dan lain-lain yang lazim diselenggarakan orang-orang Arab jauh sebelum kenabiannya. Nabi mengapresiasinya sebagaimana difirmankan, “wa kadzalika anzalnahu hukman `rabiyan (demikianlah Aku turunkan Al-Qur’an itu kepadanya berupa hukum-hukum yang telah berlaku dalam masyarakat Arab).
Sejarah mencatat, bangsa kita menerima masuknya agama-agama manapun tanpa melalui perang dan paksaan. Begitu pun Islam, orang-orang Indonesia menerima agama ini dengan damai. Mereka ini yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bahkan kini Islam menjadi agama mayoritas. Islam menyebar secara gegantis lewat pesantren-pesantren kita yang menjadi ciri khas Islam di Indonesia. Bandingkan dengan Dinasti Moghul di India. Sudah beratus tahun dinasti ini berkuasa, toh tetap gagal menjadikan Islam sebagai mayoritas di sana.
Orang-orang Indonesia masuk Islam pada masa akhir-akhir. Islam menyebar ke Maroko, Tunisia dan Asia pada abad ke-7. Islam masuk pertama kali ke Aceh pada abad ini, tetapi tidak berkembang. Justru Islam berkembangnya di Jawa pada akhir abad ke-15 atau ke-16 hingga menyebar ke seluruh Nusantara. Ini dilakukan dengan cara-cara pendidikan pesantren. Untuk pertama kalinya adalah pesantren Ampel Dento, yang serambi masjidnya bukan model Arab, melainkan mengadopsi Pendopo Brawijaya.
Apa yang diteladankan Sunan Ampel dengan pesantrennya itu, adalah Islam yang mengapresiasi budaya kita sendiri, tanpa harus meniru-niru Arab. Sehingga Islam bisa tersebar dengan damai, tanpa menyakiti awam di desa-desa karena tercerabut dari akar budayanya. Masjid yang dibangun Sunan Kudus juga mirip bangunan Pura, tempat suci agama Hindu.
Di Cirebon, masih ditemukan kantor-kantor instansi pemerintah dan masjid yang dibangun gapura di halamannya mengadopsi arsitektur candi. Islam di Jawa tidak disebarkan dengan sebentuk representasi Islam radikal a la Wahhabi seperti yang dilakukan kaum Padri di Sumatra yang mengakibatkan pertumpahan darah. Tradisi pesantren di Jawa mengajarkan cara-cara damai dalam beragama selaras dengan budaya Nusantara, tidak dengan kekerasan.
Iman dan takwa dalam al-A’raaf ayat 96 itu tidak dimaknai secara eksklusif milik orang beragama resmi Islam saja tapi inklusif. Islam yang dipakai adalah maknanya yang generik, yaitu kedamaian, kepasrahan total kepada Tuhan dan seterusnya. Apapun agama dan kepercayaannya, asalkan ia beriman dan bertakwa, artinya melakoni agama atau kepercayaannya dalam hidup sehari-hari itulah yang bisa mendatangkan berkah. Saling memperkuat dengan ayat al-A’raaf di atas, maka dalam surah al-Maidah (5:66) difirmankan: “Dan sekiranya mereka mengikuti ajaran Taurat dan Injil serta segala yang diturunkan dari Tuhan kepada mereka, niscaya mereka akan menikmati kesenangan dari setiap penjuru.”
Di ayat lain Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 62, “Orang-orang beriman (orang-orang Muslim), Yahudi, Kristen, dan Shabi’in yang percaya kepada Allah dan hari kiamat, serta melakukan amal kebajikan akan beroleh ganjaran dari Tuhan mereka. Tidak ada yang harus mereka khawatirkan, dan mereka tidak akan berduka”. (Catatan saya: terjemahan Shabi’in versi Depag adalah orang-orang yang mengikuti syariat nabi-nabi zaman dahulu atau yang menyembah bintang atau dewa-dewa). Pengertian iman dan takwa semacam ini (yaitu percaya kepada Allah, hari kiamat dan beramal kebajikan tak penting agama formalnya apa) kiranya yang dimaksudkan dalam surah al-A’raaf ayat 96 tersebut yang bisa menghadirkan keberkahan di muka bumi.
Itulah keunikan dan kearifan bangsa Indonesia yang telah terkenal sejak dulu kendati bersentuhan dengan beragam agama, namun tetap mengapresiasi dan tidak mengingkari budayanya sendiri. Kekerasan agama yang terjadi di Sumatra karena kaum Padri menolak budaya, mereka merujuk kekerasan budaya Arab.
Wali Songo yang di kemudian hari terperangkap politik kekuasaan akhirnya kembali —meminjam ejekan penulis Wedhatama di abad ke-19— “anggubel sarengat” model Arab hingga berujung pada tragedi berdarah di Jawa. Wali Songo yang dibutakan oleh kekuasaan akhirnya lupa bahwa saat Islam baru lahir, budaya kita telah mapan, telah punya desa-desa sebagai cagar budaya yang banyak jumlahnya. Mereka lupa bahwa paradigma luar tak bisa dipaksakan terhadap agama.
Tidak hanya Islam, agama manapun berkembang di negara-negara yang berbeda dengan cara-cara yang berbeda pula. Leif Manger misalnya melihat agama bukan persoalan hitam putih, bukan persoalan tunggal, milik Timur Tengah, tetapi Islam dimungkinkan melakukan dialektika yang dinamis. Antara Islam dalam kategori universal dengan lokalitas dimana ia hidup. Hal ini dikarenakan sekalipun Islam memiliki karakter universal, ia juga merupakan produk dari pergulatan dengan konteks lokal, dengan budaya setempat.
Dalam landasan budaya Nusantara inilah bangsa Indonesia yang majemuk bisa duduk bersama, itulah implementasi iman dan takwa. Jika bangsa ini bisa duduk bersama tanpa membedakan latar belakang dalam landasan budaya, maka hujan berkah tanpa diharapkan pun akan datang dengan sendirinya seperti disitir dalam surah al-A’raaf tersebut. Luar biasa, di masa lalu sepertinya Baginda Nabi telah “menyaksikan” Nusantara yang penuh berkah. Berabad-abad yang lalu, Nabi pun telah “melihat” kebangkitan Indonesia di masa depan.
Kebangkitan yang dimaksud adalah kebangkitan wajah agama yang moderat (wasatha). Kebangkitan itu adalah kebangkitan budhi (kesadaran), seperti dibilang Guru Besar dari Sumatra, Dharmakirti seribu tahun lalu. Kebangkitan itu adalah kebangkitan esensi agama-agama yang berwajah ramah, yang hormat pada Ibu Pertiwi.
Pemahaman “Islam”, “iman dan takwa” yang demikian luar biasa ini, kendati bangsa Indonesia memeluk “Islam” pada masa-masa akhir zaman persebaran Islam, karuan saja membuat Nabi Saw berdecak kagum, “A’jabu iimanan ummatin awakhiri ummati laa yudrikuunii walaa yaraaka ashaabii” (sungguh mengagumkan keimanan umat akhir zaman, yang tidak ada di zamanku dan para sahabatku
sumber : .alfisatria.